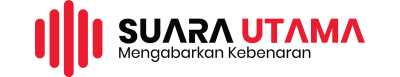Penulis Oleh : Dedek Adelia, Yulvina Sazwani dan Suhardi
PAI, Tarbiyah, IAIDU Asahan
SUARA UTAMA,Islam sebagai agama dan sekaligus sebagai sistem peradaban mengisyaratkan pentingnya pendidikan. Istilah ini terjelaskan dari berbagai muatan dalam konsep ajarannya. Salah satu di antaranya melalui pendekatan terminologis. Secara derivative Islam itu sendiri, memuat berbagai makna, salah satu di antaranya yaitu kata “Sullam” yang makna asalnya adalah tangga. Dalam kaitannnya dengan pendidikan, makna ini setara dengan makna “peningkatan kualitas” sumber daya insani (layaknya tangga, meningkat naik).
Makna Tarbiyah, Ta’lim dan Ta’dib dalam Islam

Foto Dokumentasi Mas Andre hariyanto AR.Learning Center, C.FR
Dalam perkembangan peristilahan dewasa ini terutama sejak dekade 1970an sering terjadi diskusi berkepanjangan berkenaan dengan wacana apakah Islam memiliki konsep tentang pendidikan atau tidak. Sementara para ahli berasumsi, bahwa Islam tidak memiliki konsep, karena itu maka penerapan pendidikan selama ini hanyalah mengadopsi konsep dan sistem pendidikan Barat, yang kini mendominasi sistem pendidikan secara global. Asumsi demikian tentu tidak boleh dengan serta merta disalahkan, kendatipun tidak bisa secara mutlak kita terima. Salah satu argumen yang biasa diajukan mereka adalah, karena sampai sekarang peristilahan yang secara baku dan konsisten disepakati semua pihak belumlah ada, kecuali dalam wujud polemik yang tidak berkesudahan. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin kompetitif, konsepsi tentang pendidikan terutama pendidikan Islam semakin hangat dibicarakan. Para ahli mencoba menggali peristilahan pendidikan Islam dari berbagai metode dan merumuskannya dengan berbagai istilah, terutama dari al-Quran dan al-Hadis (Al Rasyidin, 2008: 107).
Sebenarnya, konsep pendidikan menurut pandangan Islam harus dirujuk dari berbagai aspek, antara lain aspek keagamaan, aspek kesejahteraan, aspek kebahasaan, aspek ruang lingkup dan aspek tanggug jawab. Adapun yang dimaksud dengan aspek keagamaan adalah bagaimana hubungan Islam sebagai agama dengan pendidikan. Maksudnya adalah, apakah ajaran Islam memuat informasi pendidikan hingga dapat dijadikan sumber rujukan dalam penyusunan konsep pendidikan Islam. Sedangkan aspek kesejahteraan merujuk kepada latar belakang sejarah pemikiran para ahli tentang pendidikan Islam dari zaman kezaman, khususnya mengenai ada tidaknya peran Islam dalam bidang pendidikan dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan hidup manusia.Kemudian yang dimaksud dengan aspek kebahasaan adalah bagaimana pembentukan konsep pendidikan atas dasar pemahaman secara etimologi. Selanjutnya aspek ruang lingkup diperlukan untuk mengetahui tentang batas-batas kewenangan pendidikan menurut ajaran Islam. Demikian pula perlu diketahui siapa yang dibebankan tugas dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan mendidik, yaitu siapa saja yang menurut ajaran Islam dibebankan kewajiban itu.
Secara umum setidaknya ada ada tiga terma yang digunakan al-Quran dan hadits berkaitan dengan konsep dasar pendidikan dalam islam. Ketiga terma itu adalah tarbiyah, ta’lim, dan ta’dib. Meskipun sering diterjemahkan dalam arti yang sama, yakni pendidikan bahkan terkadang pengajaran, namun ketiga terma itu memiliki tekanan makna yang berbeda. Karenanya, semua terma tersebut perlu ditelaah untuk pemperoleh pemahaman yang utuh tentang hakikat pendidikan dalam islam. Untuk tujuan tersebut penulis akan mengetengahkan uraian seputar tiga terma yang maknanya selalu di nisbahkan kepada pendidikan dalam Islam.
Konsep Dasar Pendidikan Dalam Islam
Istilah pendidikan pada dasarnya berasal dari kata “didik” dengan memberi awalan “pe” dan menambah ahiran “kan” yang mengandung arti “perbuatan” (hal,cara dan sebagainya) ( WJS Poerwadarminta 1992 : 250). Istilah pendidikan ini pada mulanya berasal dari bahasa Yunani yaitu paedagogie” yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan “education” yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab, istilah ini sering diterjemahkan dengan “tarbiyah” yang berarti pendidikan. (Ramayulis 2004 : 1)
Dalam perkembangannya, istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental. Dengan demikian pendidikan berarti, segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan anak-anak untuk memimpin perkembangan jasmani dan rohaninya ke arah kedewasaan. Pengertian pendidikan Islam dilihat dari segi peristilahan, akan ditemukan beberapa istilah yang muncul dari beberapa akar kata – ditinjau dari bahasa Arab yang berbeda. Namun beberapa pengertian itu pada dasarnya mempunyai tujuan dan pengertian yang sama, yaitu mengarah kepada “pendidikan Islam”. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang peristilahan pendidikan Islam tersebut, akan di uraikan secara terminology Dari sudut pandang bahasa, pendidikan Islam berasal dari khazanah istilah bahasa Arab yang diterjemahkan, mengingat dalam bahasa itulah ajaran agama Islam diturunkan. Menurut yang tersirat dalam al-Qur‟an dan al-Hadis, dua sumber utama ajaran Islam, istilah yang dipergunakan dan dianggapnya relevan sebagai menggambarkan konsep dan aktivitas pendidikan Islam itu ada tiga, yaitu ; at-Tarbiyah, at-Ta’lim, dan at-Ta’dib. Dari ketiga Istilah tersebut term yang paling populer digunakan dalam praktek pendidikan Islam ialah term al-Tarbiyah. Sedangkan term al-Ta‟dib dan al-Ta‟lim jarang sekali digunakan. Padahal kedua istilah tersebut telah digunakan sejak awal pertumbuhan pendidikan Islam. (Samsul Nizar 2002 : 25)
BACA : Kaidah Pendidikan Menurut Islam
Tarbiyah
Tarbiyah berasal dari kata Robba, pada hakikatnya merujuk kepada Allah selaku Murabby (pendidik) sekalian alam. Kata Rabb (Tuhan) dan Murabby (pendidik) berasal dari akar kata seperti termuat dalam ayat al-Qur’an yang artinya: “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”. (Q.S. Al-Israa:24)
Kata tarbiyah, mencakup semua kegiatan pendidikan dan pengajaran dalam rangka menyiapkan individu (peserta didik), untuk kehidupan yang lebih sempurna dalam berbagai hal.
Menurut al- Yasu’iy, secara etimologis terma tarbiyah mempunyai tiga pengertian yaitu:
- Nasy’atyang berarti pertumbuhan, berusia muda meningkat dewasa.
- Taghdziyyah yang berarti member makna dan mendewasakan, dan memperkembangkan, seperti
- Yurby al shodaqah,yng berarti membuat berembang harta yang telah disedekahkan sebagaimana ungkapan surah al-Baqarah : 276 (Luis Ma’ful al-Yasu’iy 1978:247).
Menurut Syed Naquib Al-Attas, al-tarbiyah mengandung pengertian mendidik, memelihara menjaga dan membina semua ciptaan-Nya termasuk manusia, binatang dan tumbuhan. Sedangkan Samsul Nizar menjelaskan kata al-tarbiyah mengandung arti mengasuh, bertanggung jawab, memberi makan, mengembangkan, memelihara, membesarkan, menumbuhkan dan memproduksi baik yang mencakup kepada aspek jasmaniah maupun rohaniah`
Kata Rabb di dalam Al-Qur’an diulang sebanyak 169 kali dan dihubungkan pada obyek-obyek yang sangat banyak. Kata Rabb ini juga sering dikaitkan dengan kata alam, sesuatu selain Tuhan. Pengkaitan kata Rabb dengan kata alam tersebut seperti pada surat Al-A’raf ayat 61 yang artinya: “Nuh menjawab: Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan sedikitpun tetapi aku adalah utusan Tuhan semesta alam.”
Makna Tarbiyah, Ta’lim dan Ta’dib dalam Islam

Foto Dokumentasi Mas Andre Hariyanto, AR.Learning Center, C.PW
Pendidikan diistilahkan dengan ta’dib, yang berasal dari kata kerja “addaba”. Kata al-ta’dib diartikan kepada proses mendidik yang lebih tertuju pada pembinaan dan penyempurnaan akhlak atau budi pekerti peserta didik (Samsul Nizar, 2001: 90).
Istilah tarbiyah yang telah sekian abad dipergunakan memperoleh porsi sorotan lebih tajam dibanding sorotan yang pada istilah ta‟lim dan ta‟dib. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena istilah tarbiyah itulah yang dikembangkan mayoritas ahli dimana-mana sepanjang sejarah.
Dilihat dari asal bahasa, kata at-Tarbiyah mempunyai tiga asal kata ( Abdurrahman An-Nahlawi 1992 : 32). Pertama, kata tarbiyah berasal dari kata “rabba yarbu” yang berarti “zadawa nama” bertambah dan tumbuh. Kedua, berasal dari kata “rabiya-yarba” berarti “masyaa wa tara‟ra‟a” tumbuh dan berkembang. Ketiga, berasal dari kata “rabba-yarubbu” bararti “aslaluhu, tawalla amrahu, sasahu, qama „alaihi waraahu” memperbaiki, menguasai urusan, menuntut, menjaga dan memelihara. Kata al-Rabb, juga berasal dari kata Tarbiyah dan berarti “mengantarkan sesuatu kepada kesempurnaan” secara bertahap atau membuat sesuatu mencapai kesempurnaannya secara bertahap atau “membuat sesuatu menjadi sempurna” secara berangsung-angsur. (al-Raghib al-Isfahani :189). Di samping itu Abul A‟la Al-Maududi mengatakan, kata Rabbun (رب ) terdiri dari dua huruf “Ra” dan “Ba” tasydid yang merupakan pecahan dari kata tarbiyah (تربية ) yang berati “pendidikan, pengasuh, dan sebagainya”. Selain itu kata ini mencakup banyak arti seperti “kekuasaan, perlengkapan, pertanggungjawaban, perbaikan, penyempurnaan dan lain-lain”. Kata ini juga merupakan predikat bagi suatu kebesaran, keagungan, kekuasaan dan kepemimpinan. Menurut Zakiah Daradjat, (Zakiah Darajat 1992: 25-26) kata kerja Rabb yang berarti mendidik sudah dipergunakan sejak zaman Rasulullah SAW seperti dalam al-Qur‟an dan Hadis. Dalam bentuk kata benda, kata “Rabba” ini digunakan untuk “Tuhan” mungkin karena juga bersifat mendidik, mengasuh, memelihara dan mencipta.
Sesungguhnya arti kata Rabb tidak hanya dibatasi dalam makna memelihara dan membimbing, tetapi jauh lebih luas terutama
- Memelihara dan menjamin atau memenuhi kebutuhan yang dipelihara,
- Membimbing dan mengawasi serta memperbaikinya dalam segala hal,
- Pemimpin yang menjadi penggerak utamanya secara keseluruhan, Pimpinan yang diakui kekuasaannya, berwibawa dan semua perintahnya diindahkan,dan raja atau pemilik. (Abul A’la Al-Maududi 1985 : 28)
Dari sini tergambar bahwa kata Rabb yang berasal dari kata tarbiyah mengandung cukup makna yang berorientasi kepada peningkatan, perbaikan, dan penyempurnaan. Dengan demikian, kata tarbiyah itu mempunyai arti yang sangat luas dan bermacam-macam dalam penggunaannya, dan dapat diartikan menjadi makna “pendidikan, pemeliharaan, perbaikan, peningkatan, pengembangan, penciptaan dan keagungan yang kesemuanya ini menuju dalam rangka kesempurnaan sesuai dengan kedudukannya”.
Abdurrahman Al-Nahlawi menggunakan kata tarbiyah dalam pendidikan berpendapat bahwa istilah tarbiyah (pendidikan) (Abdurrahman al-Nahlawi 1979:12-14) berarti:
- Memelihara fitrah anak.
- Menumbuhkan seluruh bakat dan kesiapannya.
- Mengarahkan fitrah dan seluruh bakatnya agar menjadi baik dan sempurna.
- Bertahap dalam proses.
Berdasarkan pengertian di atas, al-Nahlawi menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tarbiyah adalah :
- Pendidikan adalah proses yang mempunyai tujuan, sasaran dan target
- Pendidik yang sebenarnya adalah Allah, karena Dialah yang menciptakan fitrah dan bakat bagi manusia. Dialah yang membuat dan memberlakukan hukum-hukum perkembangan serta bagaimana fitrah dan bakat itu berinterakasi. Dia pulalah yang menggariskan syari‟at untuk mewujudkan kesempurnaan, kebaikan dan kebahagiaan,
- Pendidik menghendaki penyusunan langkah-langkah sistematis yang harus di dahului secara bertahap oleh berbagai kegiatan pendidikan dan pengajaran.
- Pendidik harus mengikuti hukum-hukum penciptaan dan syari‟at yang telah ditentukan.
Ta’lim
Kata ta‟lim dengan kata kerja „allama juga sudah digunakan pada zaman Nabi baik di dalam al-Qur‟an maupun dalam Hadis serta pemakaian sehari-hari pada masa dulu lebih sering digunakan daripada tarbiyah. Kata „allama memberi pengertian sekadar memberi tahu atau memberi pengetahuan, tidak mengandung arti pembinaan kepribadian, karena sedikit sekali kemungkinan ke arah pembentukan kepribadian yang disebabkan pemberian pengetahuan. ( Zakiah Darajat 1992:26).
Kata Ta’lim menurut Abdul Fattah Jalal merupakan proses yang terus menerus diusahakan manusia sejak lahir. Sehingga satu segi telah mencakup aspek kognisi pada segi lain tidak mengabaikan aspek afeksi dan psikomotorik.(Abdul Fattah Jalal 1988:29) Fattah juga mendasarkan pandangan tersebut pada argumentasi bahwa Rasulullah SAW diutus sebagai Mua‟llim, sebagai pendidik dan Allah SWT sendiri menegaskan posisi Rasul-Nya yang demikian itu dalam al-Qur‟an dalam Q.S Al-Baqarah : 151 yang artinya : “Sebagaimana Kami telah mengutus kepada kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu, mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu al-Kitab dan al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui”.
Dari ayat yang tercermin di atas, dapat dipandang bahwa proses ta‟lim lebih universal dari tarbiyah. Sebab, ketika mengajarkan “tilawatil al-Qur‟an” kepada kaum muslimin Rasulullah SAW tidak sekedar terbatas pada mengajar mereka membaca, melainkan membaca disertai perenungan tentang pengertian, pemahaman, tanggung jawab da n penanaman amanah. Dari membaca semacam itu, Rasulullah SAW kemudian membawa mereka kepada tazkiyah, yakni penyucian dan pembersihan diri manusia dari segala kotoran dan menjadikan diri itu berada dalam suasana yang memungkinkannya dapat menerima hikmah, mempelajari segala yang tidak diketahui dan yang bermamfaat. Al-Hikmah tidak bisa dipelajari secara parsial dan sederhana, tetapi harus mencakup keseluruhan ilmu secara integral. Kata al-Hikmah yang berasal dari kata al-Ikham secara luas dapat diartikan sebagai keunggulan di dalam ilmu, amal, perkataan, atau di dalam semuanya itu.
BACA : Muzakarah Pemahaman Menyimpang Pada Pondok Pesantren Al-Zaytun Jawa Barat
Menuruit Rasyid Ridho, ta’lim adalah proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan ketentuan tertentu. Definisi ini berpijak pada Firman Allah yang Artinya: “ Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda seluruhnya), kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Kemudian Allah berfirman: “Sebutkanlah kepada Ku nama-nama itu jka kamu memang orang-orang yang benar. (Q.S. al-Baqarah: 31).
Rasyid Ridho memahami kata ‘allama’ sebagai proses transmisi yang dilakukan secara bertahap sebagaimana Adam menyaksikan dan menganalisis asma yang diajarkan Allah kepadanya. ta’lim mencakup fase bayi, anak-anak, remaja, dan orang dewasa. (Rasyid Ridho, 1373: 42).
Menurut Muhammad Athiyah al-Abrasy, taklim lebih khusus dibandingkan dengan tarbiyah, karena taklim hanya merupakanupaya menyiapkan individu dengan mengacu pada aspek-aspek tertentu saja, sedankan tarbiyah mencakup keseluruhan aspek-aspek pendidikan . Beberapa ayat terkait dengan kata ta’lim dalam pengertian instruction antara lain: Q.S. al-Jum’ah: 2, Q.S. al-Baqarah: 151, Q.S. al-Rahman: 1-4, Q.S. Yasin: 69, Q.S. al-Syu’ara: 49, Q.S. Thaha: 71, Q.S.al-Kahfi: 66, Q.S. Yusuf:: 6 dan 37, 68 dan 101, Q.S. al-Nisa’: 113, QS. Ali Imran: 17 dan 48, Q.S. al-Baqarah: 30, 31, 129, 239, Q.S. al-Maidah: 4 dan Q.S. al- Hujurat: 16 (al-Abrasy, 1968: 32).
Dalam pengertian lain, kata ta‟lim mempunyai konotasi khusus dan merujuk kepada “ilmu”, sehingga konsep ta‟lim itu mempunyai pengertian sebagai “pengajar ilmu” atau menjadi seorang berilmu.(Al-Jurjani:82) Secara defenitif, ilmu sebagaimana dikemukan oleh al-Jurjani dalam at-Ta‟rifati adalah:
- Ilmu adalah kesimpulan yang pasti yang sesuai dengan keadaan sesuatu.
- Ilmu adalah menetapnya ide (gambaran) tentang sesuatu dalam jiwa dan akal seseorang
- Ilmu adalah sampainya jiwa kepada hakikat sesuatu.
Dari pengertian ilmu tersebut, dapat dinyatakan bahwa konsep ta‟lim (menjadikan orang berilmu) mengandung pengertian sebagai usaha untuk memdorong dan menggerakkan daya jiwa atau akal seseorang untuk belajar (menuntut ilmu, agar sampai kepada kesimpulan, ide (gagasan) dan hakikat sebenarnya tentang sesuatu). Jadi, konsep dasar ta‟lim lebih menekankan kepada usaha untuk membelajarkan anak daripada hanya sekedar menyampaikan atau menanamkan ilmu pengetahuan.
Ta’dib
Kata Ta‟dib secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata addaba yang berarti memberi adab, mendidik. Adab dalam kehidupan sering diartikan sopan santun yang mencerminkan kepribadian (Mahmud Yunus 1992:37). Istilah ini dalam kaitan dengan arti pendidikan Islam telah dikemukakan oleh Syed Muhammad Naquib Al-Attas yang menyatakan bahwa istilah Ta‟dib merupakan istilah yang dianggap tepat untuk menunjuk arti pendidikan Islam (Muhammad Naquib Al-Attas 1994:60). Pengertian ini didasarkan bahwa arti pendidikan adalah meresapkan dan menanamkan adab pada manusia, di samping alasan makna kebahasaan lainnya. Dikemukan oleh Al-Attas bahwa pendidikan dalam kenyataannya adalah ta‟dib karena adab sebagaimana di defenisikan di sini sudah mencakup ilmu dan amal. Konsep ini di dasarkan pada hadis Nabi Artinya : “Tuhan telah mendidikku, maka Ia sempurnakan pendidikanku “ (HR. Ibnu Mas‟an dari Abi Mas‟ud).
Kata addaba dalam hadis di atas dimaknai oleh al-Attas sebagai “mendidik”. Selanjutnya ia mengemukakan, bahwa hadis tersebut bisa dimaknai kepada “Tuhan telah membuatku mengenali dan mengakui dengan adab yang dilakukan secara berangsur-angsur ditanamkan-Nya ke dalam diriku, tempat-tempat yang tepat bagi segala sesuatu di dalam penciptaan, sehingga hal itu membimbingku ke arah pengenalan-pengenalan dan pengakuan tempat-Nya yang tepat di dalam tatanan wujud kepribadian, serta sebagai sebaliknya Ia telah membuat pendidikanku yang paling baik (Muhammad Naquib Al-Atas 1994:63) .
Makna Tarbiyah, Ta’lim dan Ta’dib dalam Islam

Foto Dokumentasi Mas Andre Hariyanto, AR. Learning Center, C.PSE
Menurut Shalaby, terma ta’dîb sudah digunakan pada masa Islam klasik, terutama untuk pendidikan yang diselenggarakan di kalangan istana para khalifah. Pada masa itu, sebutan yang digunakan untuk memanggil guru adalah muaddib. Shalaby, dengan mengutip al-Jahiz, menyatakan bahwa terma muaddib berasal dari kata adab, dan adab itu bisa berarti budi pekerti atau meriwayatkan. Guru para putera khalifah disebut muaddib dikarenakan mereka bertugas mendidikkan budi pekerti dan meriwayatkan kecerdasan orang-orang terdahulu kepada mereka.
Dalam melaksanakan tugas edukatifnya, para muaddib tinggal bersama peserta didiknya. Hal itu dimaksudkan agar mereka tidak hanya sekedar mengajar, tetapi juga dapat mendidik jasmani dan ruhani peserta didik. Ibn Qutaibah, sebagaimana dikutip Shalaby, menukilkan pesan yang disampaikan Abdul Malik bin Marwan kepada muaddib puteranya: Ajarkanlah kepada mereka berkata benar, disamping mengajarkan al-Qur’an. Jauhkanlah mereka dari orang-orang jahat, karena orang-orang jahat itu tidak mengindahkan perintah Tuhan dan tidak berlaku sopan. Dan jauhkan pula dari khadam dan pelayan-pelayan, karena pergaulan dengan khadam dan pelayan- pelayan itu dapat merusakkan moralnya. Lunakkanlah perasaan mereka agar keras pundaknya. Berilah mereka makan daging, agar mereka berbadan kuat. Ajarkanlah syair kepada mereka, agar mereka mulia dan berani. Suruhlah mereka bersugi dengan melintang, dan meminum air dengan dihirup pelan-pelan, jangan diminumnya saja dengan tidak senonoh. Dan bila kamu memerlukan menegurnya, maka hendaklah dengan tertutup, jangan sampai diketahui oleh pelayan-pelayan dan tamu-tamu, agar dia tidak dipandang rendah oleh mereka. Berdasarkan kutipan di atas, tampak bahwa terma ta’dîb tidak hanya menekankan aspek pemberian ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan watak, sikap, dan kepribadian peserta didik. Karenanya, tugas seorang muaddib bukan hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga melatih dan membimbing peserta didik agar mereka hidup dengan adab, baik secara jasmani maupun ruhani. (Al Rasyidin, 2008:113-114).
Pemakaian kata ta‟dib untuk pengertian pendidikan lebih tepat dari tarbiyah dan ta‟lim menurut Al-Attas dikarenakan, Pertama¸ istilah tarbiyah yang dipahami sekarang kurang ditemukan dalam leksikon bahasa Arab besar. Ibnu Manzur merekam bentuk tarbiyah bersama dengan bentuk-bentuk lain rubba dan rabba yang diriwayatkan al-Asma‟i mengatakan istilah-istilah tersebut memuat makna yang sama (Abdurrahman Abdullah 2002: 33) . Kedua, bahwa tarbiyah berkenaan dengan istilah raba dan rabba berarti sama. Memiliki konteks hubungan dengan Tuhan misalnya, kata “Rabbayani” (Q.S. 17 : 14) bermakna rahmah, yakni ampunan dan kasih sayang. Ketiga, konsep rabba mengacu kepada kepemilikan pengetahuan bukan penanamannya. Adapun makna ta‟lim lebih berorientasi kepada pengenalan saja yang berarti “pengajaran” sedangkan yang dikehendaki dalam pendidikan Islam sampai kepada pengakuan. Di samping itu kata ta‟dib mencakup unsur pengetahuan (ilmu), pengajaran (ta‟lim), dan pengasuh yang baik (tarbiyah). Karenanya, al-Attas menganggap istilah ta‟dib lebih cepat dalam memberi makna pendidikan Islam. (Muhammad Naquib Al-Atas 1994: 64-65)
Berdasarkan argumentasi para ahli, tampaknya dalam persoalan istilah yang tepat ini pengertian pendidikan Islam-sangat tergantung kepada aspek mana dalam memandang dan memberi pemaknaannya. Semua istilah di atas mempunyai keterkaitan makna satu sama lain. Terlepas dari itu semua, yang jelas ketiga istilah ini terus menjadi khazanah intelektual muslim dalam memberikan makna pendidikan islam.
Menurut Al-Attas Konsep Pendidikan Islam lebih cenderung menggunakan istilah Ta’dib, karena dengan memilih istilah Ta’dib al-Attas menganalisisis dari sisi kandungan yang disesuaikan dengan pesan-pesan moral. Sedangkan Menurut Al-Gazali konsep pendidikan banyak berorientasi pada penekanan bathiniyah (Aspek Afektif) dari pada pengetahuan indrawi belaka, Imam Al-Ghazali memandang pendidikan sebagai sarana atau media uuntuk mendekatkan diri kepada sang pencipta dan mencapai kebahagian di dunia dan di akhirat kelak yang lebih utama. Menurut Ibnu Khuldun konsep pendidikan yaitu mencakup guru dan murid, tentang ilmu pengetahuan yang terdiri dari ilmulsa n, ilmu naqli dan Aqli tentang kurikulum dan metode.
BACA : Kopdar Pemred dan MM RSU di Warung Kopi Klotok Bahas Penerbitan Jurnal ISSN
DASAR PENDIDIKAN ISLAM
Pendidikan islami merupakan proses pemberian bantuan bagi memudahkan setiap manusia, peserta didik mengembangkan merealisasikan syahadah-nya terhadap Allah Swt. Pembuktian realisasi itu tampak dari kapasitas manusia dalam melaksanakan tujuan dan tugas penciptaannya secara sempurna, yakni sebagai ‘abd Allah dan khalifah Allah. Karena itu, pendidikan islami harus didasarkan pada landasan yang kuat, yakni dasar yang dapat dijadikan sebagai asas atau fundamen bagi pelaksanaannya
Yang dimaksud dengan dasar pendidikan adalah pandangan yang mendasari seluruh aktivitas pendidikan. Karena dasar menyangkut masalah ideal dan fundamental, maka diperlukan landasan pandangan hidup yang kokoh dan komprehensif serti tidak mudah berubah. Hal ini karena telah diyakini memiliki kebenaran yang telah diuji oleh sejarah. Karena pandangan hidup (teologi) seorang muslim berdasarkan pada al-Qur’an dan al-Sunnah, maka yang menjadi dasar pendidikan Islam adalah al-Qur’an dan al-Sunnah. Hal ini terjadi, karena dalam teologi umat Islam, al-Qur’an dan al-sunnah diyakini mengandung kebenaran mutlak yang bersifat transendental, universal, dan sternal (abadi), sehingga diyakini oleh pemeluknya akan selalu sesuai dengan fitrah manusia.
Menurut Zakiyah Daradjat, landasan pendidikan Islam adalah al-Qur’an dan sunnah nabi Muhammad saw yang dapat dikembangkan melalui ijtihad al-maslahah al-mursalah, istihsan, qiyas, dan sebagainya. Menurut Hasan langgulung yang meng utip pendapat Sa’id Ismail Ali, dasar pendidikan Islam terdiri dari 6 macam, yaitu al-Qur’an, al-sunnah, qaul shahabat, masalih al-mursalah, ‘urf dan pemikiran hasil ijtihad ientelektual muslim (Mahyuddin Barni 2008, 7 (1) ).
- Al- Quran
Pada prinsipnya, asas utama dan tertinggi yang menjadi dasar atau landasan bagi pelaksanaan pendidikan Islami adalah al-Qur’an. Karenanya, dalam konteks ini, seluruh aktivitas manusia Muslim dalam bidang pendidikan, dari mulai konsep, program, hingga praktik atau implementasinya, harus merujuk kepada konsep- konsep kunci sebagaimana dikandung al-Qur’an.
Al-qur‟an sebagai kalam Allah yang telah diriwayatkan kepada Nabi Muhammad SAW bagi pedoman masing-masing merupakan petunjuk yang lengkap mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang Universal yang mana ruang lingkupnya mencakup ilmu pengetahuanyang luas dan nilai ibadah bagi yang membacanya, yang isinya tidak dapat dimengerti kecuali dengan dipelajari kandungan yang Mulia itu. Al-Qur‟an adalah firman Allah yang diturunkan oleh malaikat jibril kepada Rosulullah SAW dengan menggunakan lafadz arab dan makna yang benar. Agar menjadi hujjah bagi Nabi Muhammad bahwa ia benar-benar Rosulullah SAW, menjadi undang-undang manusia sebagai petunjuk dan sarana untuk melakukan pendekatan diri dan ibadah kepada Allah bagi pembaca . Maka pendidikan yang didasari al-Quran adalah pendidikan yang mementingkan pembinaan pribadi dari segala seginya dan menekankan kesatuan manusia yang tidak ada perpisahan antara jasmani, akal dan perasaan.
- Hadits
Hadist adalah segala bentuk prilaku, bicara Nabi yang merupakan cara yang diteladani dalam dakwah islam yan termasuk dalam tiga dimensi yaitu; berisi ucapan. Pertanyaan dan persetujuan Nabi atas peristiwa yang teradi. Semua contoh yang ditunjukan Nabi nerupakan arah yang dapat diteladani oleh manusia demi aspek kehidupan. Posisi hadist sebagai sumber Pendidikan utama bagi pelaksanaanya Pendidikan Islam yang dijadikan referensi teoretis maupun praktis. Acuan tersebut dilihat dari dua bentuk yaitu;
- sebagai acuan syari‟ah yang meliputi muatan-muatan pokok ajaran islam secara teoretis.
- sebagai acuan oprasional aplikatif yang meliputi cara Nabi memerankan perannya sebagai pendidik yang profesional, adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran islam.
Sunnah terhadap al-Qur`an adalah sebagai penjelas. Bahkan Umar bin al-Khaththab mengingatkan bahwa Sunnah merupakan penjelasan yang paling baik. Ia berkata “ Akan datang suatu kaum yang membantahmu dengan hal-hal yang subhat di dalam al-Qur`an. Maka hadapilah mereka dengan berpegang kepada Sunnah, karena orang-orang yang bergelut dengan sunah lebih tahu tentang kitab Allah SWT.
Dengan adanya sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah al-Quran, maka dalam pendidikan apa yang dijelaskan Rasulullah baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqrir akan menjadi sumber dasar dalam pendidikan baik sebagai simtem pendidikan maupun metodologi pendidikan Islam yang harus dijalani. Apalagi secara ilmiah, Rasulullah dengan al-Quran dan penjelasan Rasul berupa sunnah selama 23 tahun saja dapat sukses melakukan perubahan peradaban masyarakat Arab dari Jahiliyah menjadi peradaban madani. Padahal biasanya perdaban itu dibentuk minimal 100 tahun yang telah berjalan (Abdurrahman al-Nahlawi 1979: 23-24)
- Ijtihad
Selain kedua sumber di atas, al-Qur’an dan Hadis, asas yang digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan pendidikan Islami juga bersumber dari hasil-hasil ijtihad, kontemplasi, atau pemikiran para ulama atau ilmuan Muslim. Secara luas, ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh yang dilakukan para pemikir atau intelektual Muslim-dengan mengerahkan daya atau energi intelektualnya- dalam melakukan penalaran mendalam, sistematis, dan universal untuk memamahi hakikat atau esensi sesuatu (Al Rasyidin, 2008:128).
Pendidikan sebagai lembaga sosial akan turut mengalami perubahan sesuai dengan perubahan yang tejadi di masyarakat. Kita tahu perubahan-perubahan yang ada di zaman sekarang atau mungkin sepuluh tahun yang akan datang mestinya tidak dijumpai pada masa Rasulullah saw, tetapi memerlukan jawaban untuk kepentingan pendidikan di masa sekarang. Untuk itulah diperlukan ijtihad dari pendidik muslim. Dasar hukum yang memboleh ijtihad dengan penggunaan ra’yu adalah sebuah hadits percakapan Rasulullah dengan Muaz bin Jabal ketika akan diutus di Yaman. Artinya,” Hai Muaz: Jika engkau diminta memutuskan perkara, dengan apakah engkau memutuskannya?”. Muaz menjawab; dengan Kitab Allah (al-Quran), maka Rasulullah bersabda; Kalau engkau tidak mendapati (dalam al-Quran itu)” kata Muaz: “dengan Sunnah Rasulullah”, Rasulullah bersabda kembali; Jika engkay tidak mendapati di situ?’ Muaz menjawab,” Saya berijtihad dengan pendapatku dan tidak akan kembali”. Ijtihad pada dasarnya merupakan usaha sungguh- sungguh orang muslim untuk selalu berprilaku berdasarkan ajaran Islam. Untuk itu manakala tidak ditemukan petunjuk yang jelas dari al-Qur`an ataupun Sunnah tentang suatu prilaku ,orang muslim akan mengerahkan segenap kemampuannya untuk menemukannya dengan prinsip-prinsip al-Qur`an atau Sunnah.
Melakukan ijtihaj dalam pendidikan islam sangatlah perlu,karena media pendidikan mer upakan sarana utama dalammembangun pranata kehidupan social dalam arti maju mundurnya kebudayaan manusia berkembang secara dinamis sangat ditentukan dari dinamika system pendidikan yang dilaksnakan. Dalam dunia pendidikan sumbangan ijtihad dalam keikut sertaannya menata system pendidikan yang ingin di capai, sedangkan untuk perumusan system pendidikan yang dialogis dan adaptik, baik karena pertimbangan perkembangan zaman maupun kebutuhan manusia dengan berbagai potensi diperlukan upaya maksimal. Proses ijtihad harus merupakan kerja sama yang utuh di antara Mujtahid (Syaiful Anwar 2015 : 10-11) .
Berikutnya dasar hasil dari ijtihad adalah mashlahah mursalah (kemaslahatan umat) yaitu menetapkan peraturan atau ketetapan undang-undang yang tidak disebutkan dalam al-Quran dan as-Sunnah atas pertimbangan penarikan kebaikan dan menghindarkan kerusakan ( Ramayulis 2010: 129). Penarikan kebaikan dan menghindar kerusakan bisa diterima selama tidak menyalahi keberadaan-keberadaan al-Quran dan as-Sunnah,benar-benar membawa kemaslahatan. Mashlahah mursalah ini, menurut Abdul Wahhab Khallaf dalam Ramayulis, diterima sebagai dasar pendidikan Islam selama tidak menyalahi keberadaan al-Quran dan as-Sunnah, benar-benar membawa kemaslahatan, menolak kemudaratan setelah melalui tahapan observasi, dan kemaslahatan yang bersifat universal untuk totalitas masyarakat(Ramayulis 2010: 129).
Selain mashlahah mursalah yang dapat menjadi dasar pendidikan Islam hasil ra’yu adalah berupa ‘Urf, yaitu nilai-nilai dan istiadat masyarakat. Menurut Al Sahad al-Jundi dalam Ramayulis, ’Urf diartikan sesuatu yang tertanam dalam jiwa berupa hal-hal yang berulang dilakukan secara rasional menurut tabiat yang sehat (Ramayulis 2010: 130). Dasar pendidikan dengan mashlahah mursalah dan ‘urf ini dapat dijadikan asas pendidikan selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan as-Sunnah.
Dalam tataran praktikal, para ulama atau intelektual Muslim melakukan ijtihad adalah untuk mendapatkan kebenaran tentang sesuatu hal, ketika sumber kebenaran yang lebih tinggi-al-Qur’an dan Hadis-tidak memberikan informasi atau penjelasan yang lebih rinci mengenai hal tersebut. Karenanya, dalam konteks pendidikan islami, kedudukan ijtihad menempati urutan ketiga – setelah al- Qur’an dan Hadis – sebagai landasan bagi perumusan gagasan atau pemikiran, penyusunan program, dan pelaksanaan praktik pendidikan islami. Dalam konteks ini, dari satu sisi, harus dipahami bahwa ijtihad atau hasil-hasil pemikiran para ulama atau intelektual Muslim hanyalah sebagai upaya untuk menalar atau memahami secara lebih baik dan mendalam’ isyarat-isyarat yang dikemukakan al-Qur’an dan Hadits berkaitan dengan pendidikan islami. Sedangkan dari sisi lain, ijtihad atau hasil-hasil pemikiran para ulama atau intelektual Muslim hanyalah sebagai upaya untuk menalar atau menangkap secara lebih baik dan mendalam’ setiap ‘denyut’ perubahan yang sedang dan bakal terjadi dalam kehidupan manusia sepanjang perjalanan kesejarahannya (Al Rasyidin, 2008:128).
Makna Tarbiyah, Ta’lim dan Ta’dib dalam Islam

Foto Dokumentasi Suhardi, Tinjauan Tarbiyah, Ta’lim dan Ta’dib.
Dasar pendidikan islam dimulai dari pengetahuan dalam masyarakat atau lingkungan sehari-hari dengan itu akan timbul ilmu pengetahuan pada siri seseorang. Salah satu penopang keberhasilan Negara yaitu dengan adanya Pendidikan dalam hal ini pendidikan islam sangat berperan bagi kemajuan suatu Negara. Melihat sangat pentingnya sebuah pendidikan bahkan diriwayatkan suatu hadist Nabi, yang menganjurkan kita untuk menuntut ilmu dengan ilmu pengetahuan. Sebab dengan kita memiliki ilmu seseorang akan dapat mengetahui barang yang benar dan yang salah, dapat mengetahui perintah dan larangan Allah, sehingga dapat melakukan perintah-perintah Allah dengan baik, benar dan sempurna, menjadikan amal perbuatannya diterima oleh Allah dan diberikan pahala disyurga.
Mengamalkan apa yang sudah kita dapat dengan harapan niat untuk taqwa pada Allah, beribadah pada Allah, maka akan semakin dalam kita menuju kecintaan pada Allah dan ridlonya dengan apa yang kita kerjakan baik dhohir maupun batin.
Selain asas-asas di atas, dalam tataran operasionalnya, asas yang digunakan bagi pelaksanaan pendidikan islami setidaknya mencakup pula landasan historis, sosiologis, ekonomis, politik dan administrasi, psikologis, dan filosofis. Asas historis adalah landasan pelaksanaan pendidikan islami yang mengacu kepada pengalaman kesejarahan umat Islam masa lalu dalam menyelenggarakan pendidikan islami. Adapun asas sosiologis adalah landasan yang memberikan kerangka sosio-budaya bagi pelaksanaan pendidikan islami. Agar berhasil dalam pelaksanaannnya, bagaimanapun, pendidikan islami harus memahami karakter dasar masyarakat, budaya, dan sistem-sistem sosialnya. Kemudian yang dimaksud asas ekonomis adalah landasan yang memberikan perspektif tentang potensi-potensi finansial, menggali, mengatur, dan mengembangkan sumber-sumber bagi pembiayaan pendidikan islami. Karena pendidikan islami ditujukan pada upaya mengantarkan manusia kepada syahadah primordialnya yang suci, maka sumber-sumber finansial bagi pembiayaan dan kontinuitas pendidikan islami haruslah bersih, suci, dan tidak tercampur dengan sesuatu yang syubhat. Selanjutnya yang dimaksud dengan asas politik dan administrasi adalah landasan yang digunakan untuk merumuskan dan menentukan kebijakan-kebijakan dalam penataan dan penyelenggaraan praktik pendidikan islami, baik dalam level makro maupun mikro. Sedangkan asas psikologi adalah landasan yang digunakan sebagai rujukan dalam memahami bak at, minat, watak, karakter, dan perbedaan-perbedaan individual di antara manusia peserta didik yang akan dibantu mengembangkan diri dan potensi yang dimilikinya sehingga mereka berkemampuan bersyahadah Tuhan. Seterusnya yang dimaksud dengan asas filosofis adalah landasan yang digunakan dalam memahami esensi, tujuan, dan semua komponen yang berkaitan dengan pendidikan islami. Asas ini merupakan landasan yang membingkai dan mengintegrasikan seluruh operasional pendidikan islami sebagaimana dikemukakan di atas (Al Rasyidin, 2008:128).
Kesimpulan
Dari keterangan-keterangan di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Konsep Pendidikan Islam bermuara dalam dasar, tujuan, aspek-aspek serta realisasi sebagai bukti atas teori yang harus dibuktikan.
Yang dimaksud dengan dasar pendidikan adalah pandangan yang mendasari seluruh aktivitas pendidikan. Karena dasar menyangkut masalah ideal dan fundamental, maka diperlukan landasan pandangan hidup yang kokoh dan komprehensif serti tidak mudah berubah.
Meskipun sudah dikenal sejak lama, bahkan digunakan dalam praktik pendidikan masa awal Islam, istilah ta’dib untuk menyebutkan makna pendidikan dalam Islam digagas dan dipopulerkan kembali oleh Syed Mohammad Naquib al-Attas, guru besar dan pendiri International Institute of Islamic Thought and Civilization, Malaysia. Menurut al-Attas, kata ta’dib merupakan terma yang paling benar untuk menyebutkan istilah pendidikan dalam konteks Islam. Penggunaan terma ta’dib (b) untuk istilah yang paling sesuai untuk pendidikan dalam Islam didasarkan pada hadis Rasulullah Saw yang artinya: Tuhanku telah mendidikku dan menjadikan pendidikanku sebaik-baik pendidikan.
BACA : Alumni IAIDU Sabet Juara Karya Tulis Ilmiah AlQuran Tingkat Kabupaten Asahan
Berdasarkan argumentasi para ahli, tampaknya dalam persoalan istilah yang tepat ini pengertian pendidikan Islam-sangat tergantung kepada aspek mana dalam memandang dan memberi pemaknaannya. Semua istilah di atas mempunyai keterkaitan makna satu sama lain. Terlepas dari itu semua, yang jelas ketiga istilah ini terus menjadi khazanah intelektual muslim dalam memberikan makna pendidikan islam.
Dalam konteks pendidikan islami, seluruh ide, pandangan, konsep, teori, konstitusi, dan praktik pendidikan harus merujuk kepada apa yang ditunjuk, dijelaskan, diidentifikasi, digaris bawahi dirumuskan, dan disimpulkan oleh al-Qur’an. Untuk mampu menangkap isyarat dan rumusan-rumusan al-Qur’an tentang pendidikan islami tersebut, maka manusia harus menginterpretasi Al-Qur’an. Proses tersebut bisa dilakukan melalui penalaran logika yang mendalam, sistematis, dan universal. Di samping itu, proses interpretasi juga bisa dilakukan melalui survey yang cermat dan mendalam terhadap hadis-hadis nabi Saw dan contoh atau praktik yang ditampilkan para shahabah.
Tujuan tertinggi yang ingin dicapai oleh pendidikan islami adalah menciptakan manusia Muslim yang bersyahadah kepada Allah Swt. Karenanya dalam tatanan praktikal, seluruh program dan praktik pendidikan islami diarahkan untuk memberikan bantuan kemudahan kepada semua manusia dalam mengembangkan potensi jismiyah dan ruhiyahnya sehingga mereka berkemampuan mengaktualisasikan syahadahnya terhadap Allah Swt. Dalam perspektif falsafah pendidikan islami, aktualisasi syahadah tersebut harus ditampilkan dalam kemampuan manusia Muslim menunaikan fungsinya sebagai ‘abd Allah dan melaksanakan tugas-tugasnya sebagai khalifah secara sempurna. Profil manusia Muslim seperti inilah yang populer disebut sebagai insan kamil atau manusia paripurna.
Mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa merupakan satu satunya tujuan akhir yang dimaksudkan kepada seluruh manusia, Karena pada hakikatnya seluruh alam yang diciptakan ini sebagai alat dan sarana bagi manusia untuk membina dan membentuk diri menjadi manusia yang bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Keberadaan manusia di atas permukaan bumi ini merupakan satu bukti kekuasaan allah, oleh karenanya pendidikan islam menuntun untuk menjadikan setiap insan manusia menjadi manusia yang sesungguhnya yaitu manusia yang selalu beriman dan bertaqwa kepada Allah dengan pencapaian kehidupan yang bahagia baik di dunia dan akhirat.
Sekian dari penulis sekiranya jika terdapat kesalahan pada penulisan di atas para pembaca (viewer/readers) boleh memberika kritik dan sarannya kepada penulis yang mana dengan kritik dan saran dari para pembaca penulis bisa menjadi lebih baik lagi kedepannya.