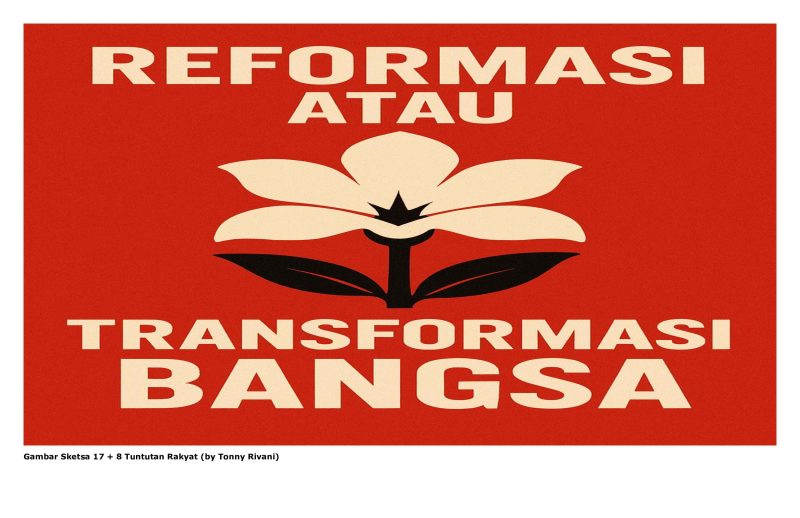SUARA UTAMA –
Suara yang Menggema dari Medsos
Beberapa hari terakhir, jagat media sosial Indonesia diramaikan oleh satu dokumen yang viral: “17+8 Tuntutan Rakyat”. Sejak muncul akhir Agustus 2025, ia dengan cepat menyalakan diskusi publik, menyulut aksi mahasiswa, serikat buruh, hingga mendorong berbagai organisasi sipil angkat bicara.
Dokumen ini merangkum 17 tuntutan jangka pendek yang diberi tenggat 5 September 2025 dan 8 tuntutan jangka panjang yang diharapkan tercapai paling lambat 31 Agustus 2026. Di baliknya ada semangat yang sama: kegelisahan rakyat terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak, praktik politik yang jauh dari etika, serta penanganan aksi massa yang menelan korban jiwa.
Kasus tragis meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang terlindas rantis Brimob saat demonstrasi, menjadi pemicu solidaritas nasional. Ia bukan sekadar simbol korban, melainkan penanda bahwa relasi negara–warga kembali dipertanyakan.
Apa Isi 17+8 Tuntutan Itu?
17 tuntutan jangka pendek menitikberatkan pada langkah cepat:
- Tarik TNI dari pengamanan sipil dan hentikan kriminalisasi demonstran.
- Bentuk tim investigasi independen atas korban aksi, termasuk kasus Affan.
- Hentikan kekerasan polisi dan bebaskan demonstran yang ditahan.
- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR, audit kinerja, dan transparansi anggaran.
- Ambil langkah darurat ekonomi untuk melindungi pekerja dari PHK dan menjamin upah layak.
Sementara 8 tuntutan jangka panjang menyentuh akar persoalan:
- Reformasi DPR: audit independen, hapus fasilitas mewah, larangan mantan koruptor kembali berpolitik.
- Reformasi partai politik dan penguatan pengawasan eksekutif.
- Sahkan UU Perampasan Aset Koruptor dan perkuat independensi lembaga antikorupsi.
- Profesionalisasi Polri dan TNI kembali ke fungsi pertahanan.
- Tinjau ulang kebijakan pembangunan yang merugikan rakyat, dari UU Cipta Kerja hingga proyek strategis nasional.
Dari daftar itu terlihat jelas, publik tidak hanya menuntut keadilan atas insiden aksi, tetapi juga mendorong perubahan sistemik.
Pandangan Pakar dan Akademisi
Sejumlah akademisi menilai gerakan 17+8 adalah akumulasi kekecewaan publik. Profesor politik dari UGM menyebutnya sebagai “ledakan sosial digital”: lahir dari kanal medsos, namun beresonansi ke jalanan.
Pakar hukum menekankan urgensi investigasi independen. “Jika negara abai, ia bukan hanya kehilangan kepercayaan, tapi juga membuka ruang bagi kekerasan yang lebih luas,” ujar seorang ahli HAM dari UI.
Ekonom menyoroti tuntutan soal upah dan perlindungan buruh sebagai alarm serius. Dalam kondisi ekonomi yang rentan, keengganan pemerintah merespons dapat melahirkan instabilitas baru.
Pandangan Media Nasional
Media arus utama merangkum dua sisi penting. Pertama, isi tuntutan yang menyuarakan perombakan tata kelola politik dan ekonomi. Kedua, fakta lapangan bahwa aparat dan demonstran kerap berhadap-hadapan secara keras.
Detik, CNN Indonesia, Kompas, dan Tempo menegaskan bahwa 17+8 bukanlah sekadar tren medsos, melainkan pernyataan politik rakyat. CNBC bahkan menyoroti potensi dampak ekonomi jika isu tuntutan diabaikan, mulai dari pelemahan kepercayaan investor hingga ancaman gejolak pasar.
Suara Ormas Keagamaan dan Sipil
Organisasi Islam besar seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengimbau agar elit berintrospeksi. Muhammadiyah menegaskan pentingnya empati dan keterbukaan, sementara NU menekankan agar aparat dan rakyat sama-sama menahan diri demi menghindari pertumpahan darah.
Di sisi lain, sejumlah ormas sipil dan LSM hak asasi menyambut positif 17+8 sebagai bentuk partisipasi demokrasi generasi muda. Mereka menekankan bahwa pemerintah sebaiknya mendengar bukan menindas.
Perguruan Tinggi dan Gerakan Mahasiswa
Ratusan BEM dari berbagai kampus menyatakan dukungan moral terhadap substansi 17+8. BEM se-UI, ITB, dan UGM mendorong adanya forum dialog terbuka antara mahasiswa dan pemerintah.
Universitas sendiri mengambil posisi hati-hati: menjaga keselamatan civitas akademika, namun juga mengakui pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam demokrasi. Para akademisi berharap kampus bisa menjadi jembatan diskusi yang mendorong transformasi kebijakan, bukan sekadar menjadi arena benturan fisik.
Dampaknya bagi Demokrasi
Gerakan 17+8 bisa dibaca sebagai cermin krisis kepercayaan rakyat terhadap lembaga perwakilan. DPR dituntut menunda kenaikan tunjangan, membuka transparansi, dan membuktikan diri bukan sekadar lembaga penghabis anggaran.
Kedua, ia menandai lahirnya model partisipasi baru: tuntutan lahir dari medsos, menyebar lewat poster digital, lalu menekan politik formal. Ini menantang demokrasi konvensional yang selama ini berjalan lamban dan elitis.
Ketiga, isu supremasi sipil atas aparat kembali diuji. Desakan agar TNI kembali ke barak dan Polri menghentikan kekerasan bukan hal baru, tetapi kali ini digaungkan secara massif dan terkoordinasi. Jika diabaikan, legitimasi demokrasi bisa semakin rapuh.
Keempat, ada risiko polarisasi. Jika tuntutan tidak dijawab dengan dialog dan tindakan nyata, muncul ruang bagi seruan ekstrem seperti pembubaran lembaga negara. Gerakan yang semula aspiratif bisa berubah menjadi destruktif.
Menjawab Tuntutan, Bukan Membungkam
Pemerintah dan DPR dihadapkan pada pilihan penting: mendengar atau menolak. Mengabaikan 17+8 hanya akan memperlebar jarak rakyat dan elit.
Langkah realistis yang bisa segera diambil antara lain:
- Membekukan kenaikan tunjangan DPR dan membuka audit independen.
- Mengumumkan investigasi transparan terhadap kasus Affan dan pelanggaran aparat.
- Membebaskan demonstran yang ditahan tanpa dasar kuat.
- Membuka forum dialog resmi dengan perwakilan mahasiswa, buruh, dan LSM.
Tindakan sederhana namun nyata ini bisa mengubah tensi politik sekaligus mengembalikan sedikit kepercayaan rakyat.
Penutup: Suara Demokrasi di Era Digital
“17+8 Tuntutan Rakyat” bukanlah sekadar angka atau dokumen viral. Ia adalah simbol keresahan yang menuntut jawaban.
Dalam demokrasi, suara rakyat tidak selalu hadir lewat bilik suara pemilu. Kadang ia lahir dari jalanan, kadang dari kampus, kini juga dari media sosial. Menyikapi suara itu dengan empati dan keterbukaan akan menguatkan demokrasi. Sebaliknya, menutup telinga hanya akan mempercepat keruntuhan legitimasi.
Hari-hari ini, Indonesia diuji: apakah demokrasi kita cukup matang untuk mendengar jeritan rakyat, atau justru tergelincir ke siklus lama — ketika kritik dibungkam dan aspirasi diabaikan.
Sejarah akan mencatat pilihan itu.